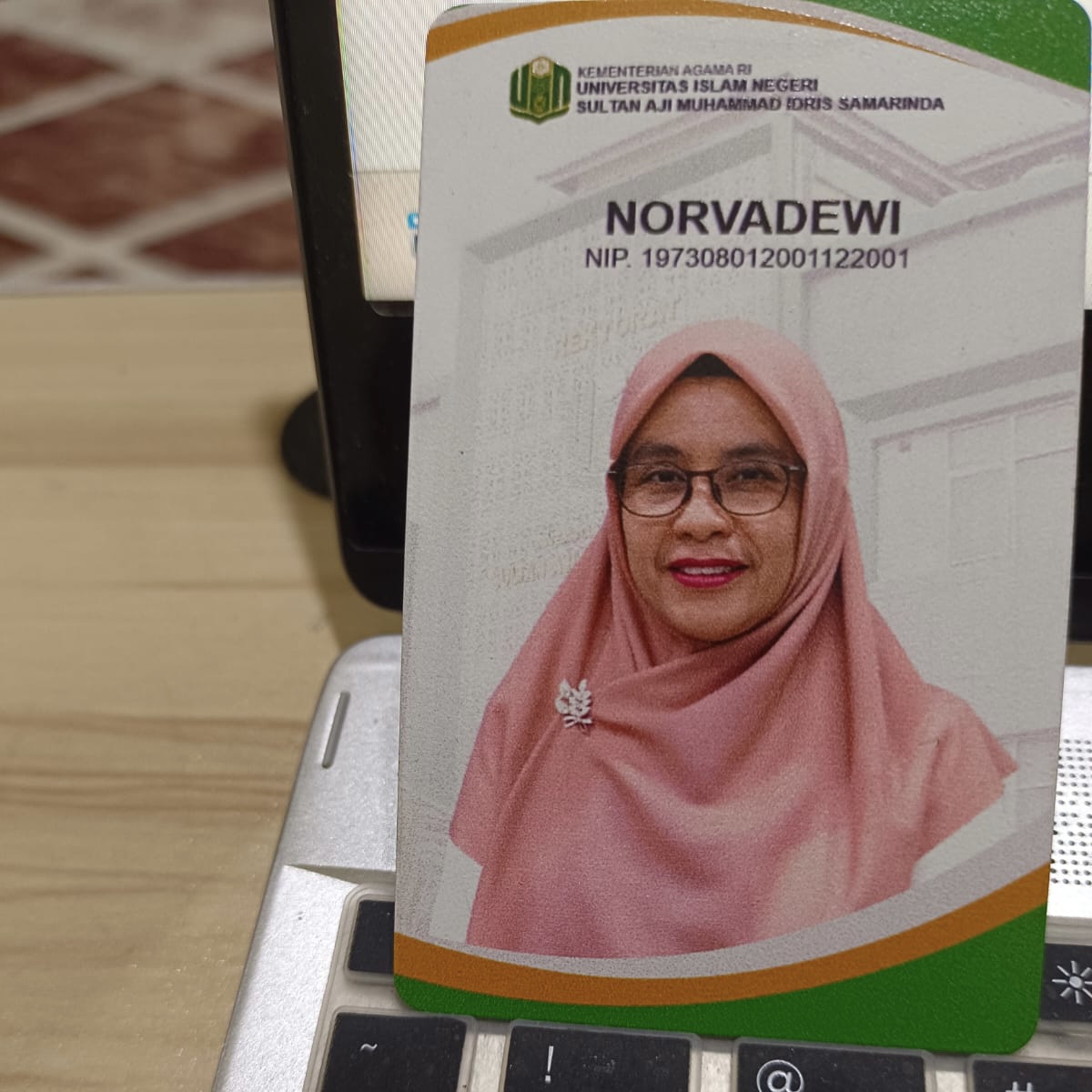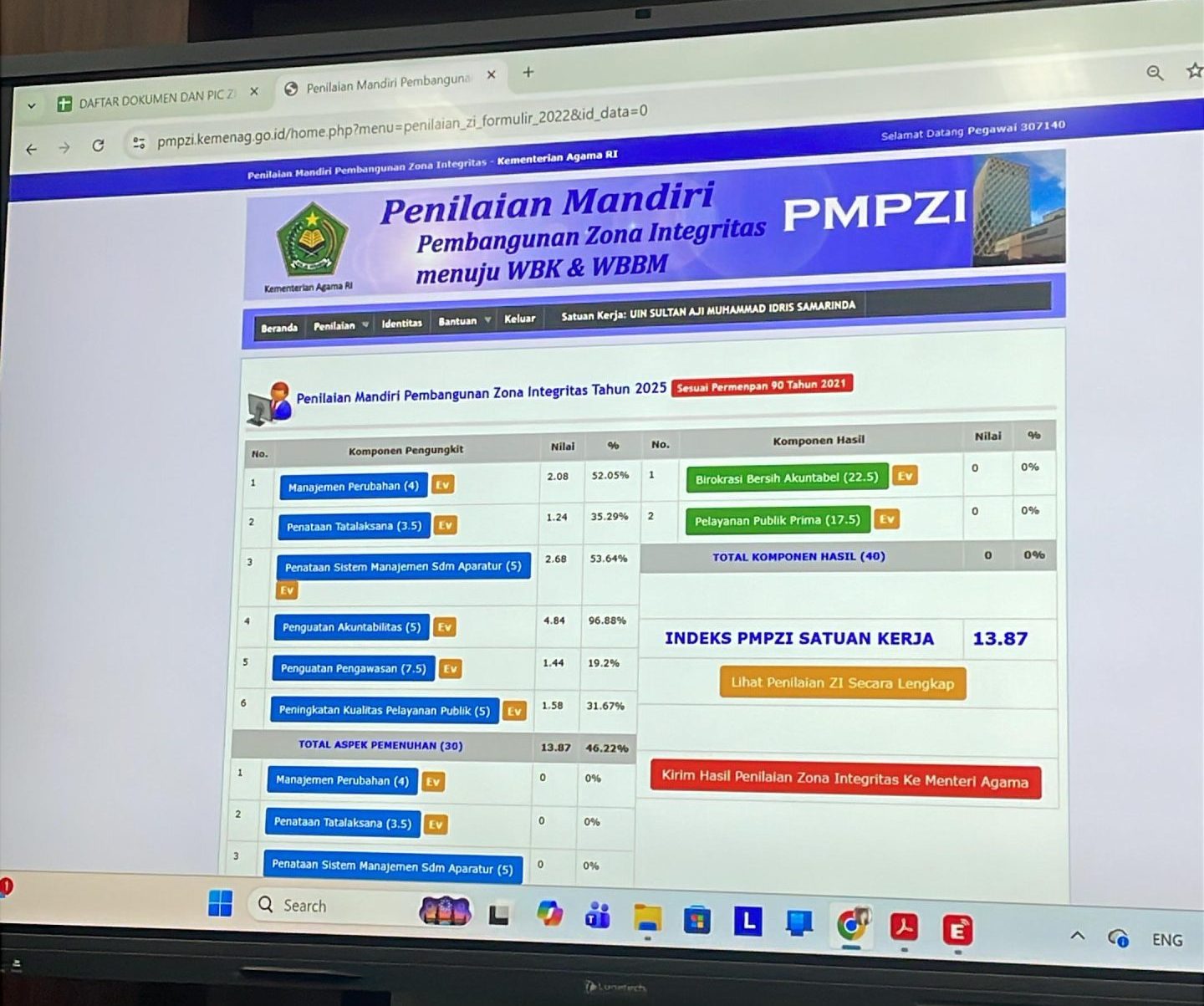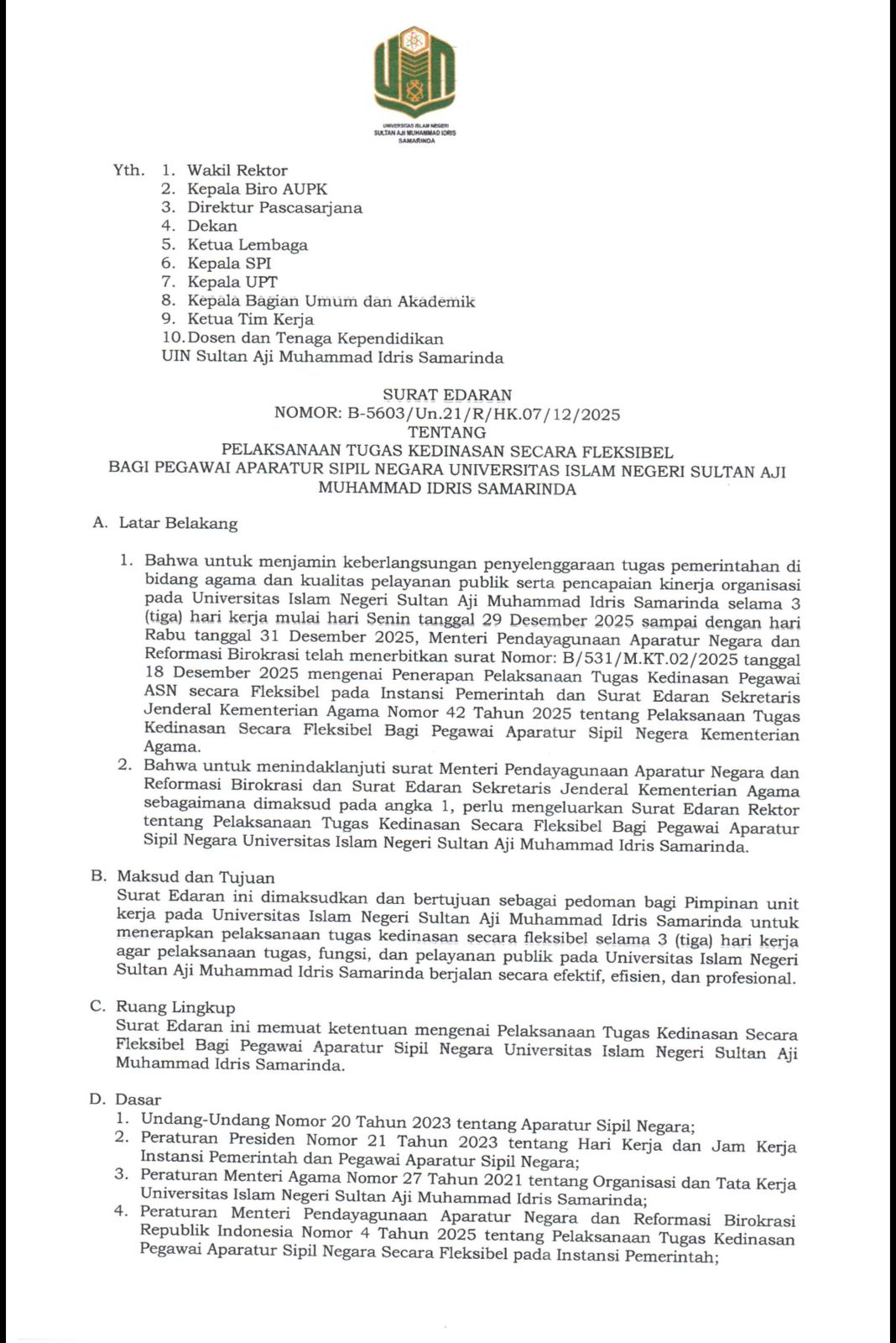Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah qurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Adha telah menjadi bagian dari budaya keagamaan yang mengakar kuat dalam masyarakat. Namun saat ini dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi yang kompleks: inflasi, krisis pangan, ketimpangan distribusi, dan ancaman resesi termasuk bencara alam membayangi banyak negara. Di tengah situasi ini, sebagian masyarakat mempertanyakan apakah qurban masih relevan untuk dilaksanakan. Jawabannya justru sebaliknya. Qurban tetap penting, bahkan menjadi lebih signifikan. Islam tidak pernah memaksakan ibadah ini bagi yang tidak mampu, namun bagi yang memiliki kelapangan rezeki, qurban menjadi ladang pahala dan sarana kontribusi sosial yang nyata. Dibalik ritual ibadah qurban, terdapat makna yang jauh lebih dalam. Qurban bukan hanya simbol ketundukan spiritual, namun sebuah potensi besar sebagai strategi distribusi kekayaan dan penguatan ekonomi umat.
Secara prinsip, qurban mengajarkan pengorbanan, ketulusan, dan keberanian meninggalkan kecintaan terhadap harta demi meraih keridhaan Allah. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan di tengah krisis, ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan materialisme, individualisme, dan ketimpangan. Dalam qurban, seseorang rela mengeluarkan hartanya bukan untuk investasi duniawi, tetapi demi manfaat sosial dan spiritual yang lebih luas. Daging qurban yang dibagikan kepada fakir miskin bukan hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan pengakuan terhadap eksistensi kaum lemah dalam struktur sosial.
Dari perspektif ekonomi Islam, qurban bukan sekadar ibadah ritual. Ia memiliki nilai distribusi kekayaan yang kuat. Ketika umat Islam berqurban, terjadi perputaran ekonomi yang nyata: peternak lokal diuntungkan, pedagang hewan mendapat penghasilan, membuka lapangan kerja temporer (juru sembelih, distribusi, pengemasan), dan masyarakat miskin menerima manfaat langsung. Qurban mendorong permintaan domestik di sektor peternakan dan pangan, yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi mikro umat. Maka, qurban seharusnya tidak dipandang sebagai beban finansial, melainkan sebagai sumbangsih terhadap keberlanjutan ekonomi berbasis umat.
Qurban juga membentuk filantropi Islam yang terorganisir. Lembaga-lembaga zakat dan sosial kini mengelola program qurban secara kolektif dengan pendekatan produktif. Model pengelolaan qurban telah berkembang seperti “Qurban Berdaya”, “Qurban Ternak Mandiri”, atau “Tabungan Qurban” hingga distribusi lintas wilayah dan negara. Inovasi-inovasi ini memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi, bahkan dengan nominal yang terjangkau. Kampus-kampus Islam pun dapat mengambil peran penting dalam gerakan ini. Melalui qurban kolektif, dosen, mahasiswa, dan staf bisa bersama-sama menjalankan ibadah sekaligus menunjukkan solidaritas sosial. Lebih dari itu, kampus dapat menjadi pusat edukasi qurban yang berbasis nilai-nilai maqashid syariah dan ekonomi Islam.
Selain itu ibadah qurban juga memiliki dimensi edukatif yang tak kalah penting. Ia mengajarkan nilai kepemimpinan, pengorbanan, dan empati sosial. Mahasiswa sebagai calon pemimpin umat perlu memandang qurban bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai pelatihan moral dan spiritual. Dengan ikut serta dalam program qurban, mereka belajar mengelola keuangan, merencanakan pengeluaran, dan berpikir jangka panjang tentang dampak sosial dari tindakan individu. Di sinilah peran lembaga kampus sangat vital: menjadikan momen Idul Adha sebagai bagian dari penguatan karakter Islami dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam konteks akademik, qurban dapat dikaji dari berbagai sudut. Mahasiswa ekonomi syariah bisa meneliti dampak qurban terhadap perekonomian lokal. Mahasiswa sosiologi dapat mengamati peran qurban dalam memperkuat solidaritas antar lapisan masyarakat. Mahasiswa dakwah bisa mengeksplorasi cara-cara menyampaikan pesan-pesan spiritual qurban yang kontekstual dan membumi. Qurban dapat menjadi tema lintas disiplin yang kaya untuk dijadikan bahan kajian, riset, dan aksi sosial.
Lebih jauh, penting disadari bahwa qurban adalah bentuk aktualisasi dari konsep falah dalam Islam. Falah berarti kebahagiaan yang paripurna, mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketika seseorang berqurban, ia sedang menapaki jalan falah—berbagi dari yang dimiliki, mengurangi cinta terhadap dunia, dan menumbuhkan cinta kepada sesama. Dalam kondisi krisis global, nilai-nilai inilah yang paling dibutuhkan umat. Qurban menjadi terapi spiritual sekaligus kontribusi ekonomi yang sangat relevan.
Qurban juga mengajarkan bahwa harta bukan untuk dikumpulkan semata, tetapi untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan. Konsep barakah (keberkahan) dalam Islam menunjukkan bahwa nilai sebuah harta bukan pada jumlahnya, tetapi pada sejauh mana ia memberikan manfaat. Ketika seseorang menyisihkan sebagian hartanya untuk qurban, ia sedang menanam investasi ukhrawi yang tidak akan pernah merugi. Bahkan dalam kondisi ekonomi sulit, Allah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang berinfak di jalan-Nya.
Sebagai penutup, sudah saatnya umat Islam, terutama generasi intelektual muda di kampus, memaknai qurban lebih dari sekadar ritual tahunan. Dalam situasi sulit, qurban justru bukan menjadi beban, melainkan peluang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang solutif, peduli, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Qurban menjadi bukti nyata bahwa dalam kondisi keterbatasan, umat Islam tetap diajarkan untuk memberi, berbagi, dan menjaga martabat saudara-saudaranya. Sebab dalam Islam, keberkahan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang mampu ditebarkan kepada sesama. Dari ritual ke strategi umat, inilah saatnya qurban dimaknai dan dioptimalkan sebagai solusi integral berbasis tauhid, adil, dan maslahah. Mari Mari kita optimalkan ibadah ini dengan kesadaran penuh akan nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan yang dikandungnya.
Penulis: Dr. Hj. Norvadewi, M.Ag. (Dosen FEBI UINSI Samarinda)