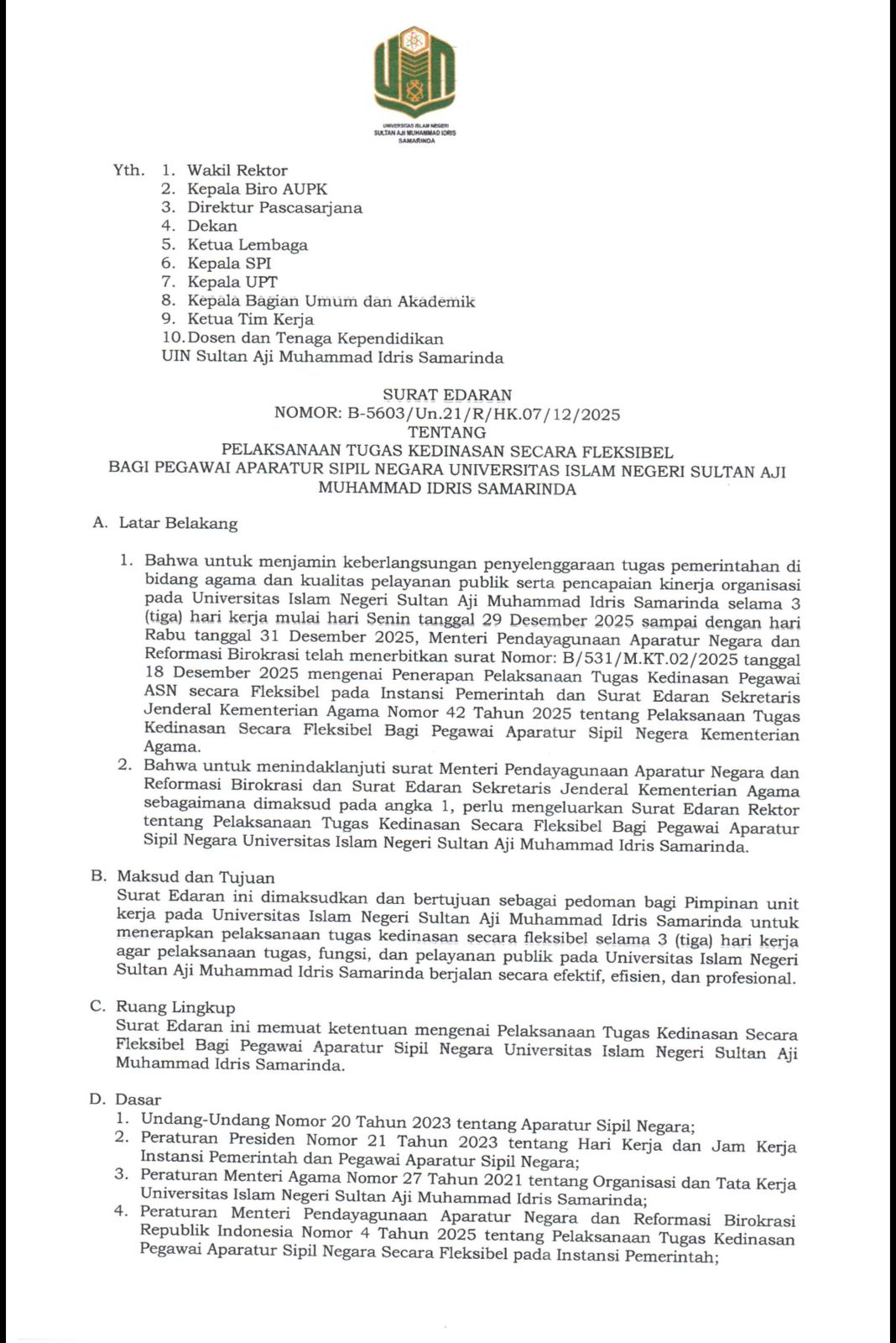Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Praktik yang merugikan keuangan negara ini seolah menjadi budaya yang sulit diberantas secara tuntas. Hampir setiap tahun, kasus korupsi bermunculan dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga aparatur penegak hukum. Sementara itu, masyarakat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan pada para pelaku. Banyak dari mereka yang setelah menjalani hukuman, tetap bisa menikmati hasil korupsinya, hidup mewah, bahkan kembali aktif di dunia politik.
Ironi ini mencerminkan satu fakta yang tak terbantahkan: hukum kita belum sepenuhnya mampu menjerat koruptor dengan efek jera yang nyata. Hukuman penjara saja tidak cukup. Sudah waktunya negara mengambil langkah lebih tegas dan sistematis untuk memastikan bahwa korupsi tidak menjadi jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan. Dalam konteks inilah, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi sangat mendesak untuk segera disahkan menjadi undang-undang.
RUU Perampasan Aset bukanlah wacana baru. Ia telah lama berada dalam daftar Program Legislasi Nasional, namun pembahasannya selalu stagnan. Padahal, peraturan ini merupakan instrumen penting dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, terutama korupsi. Salah satu kekuatan utama dari RUU ini adalah memungkinkan negara untuk merampas aset hasil kejahatan meskipun pelaku belum divonis bersalah oleh pengadilan pidana. Mekanisme ini dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture, dan telah diterapkan di berbagai negara sebagai cara yang efektif menghadapi kejahatan transnasional dan terorganisir. Melalui pendekatan ini, negara tidak lagi bergantung pada putusan pidana yang seringkali berlarut-larut, penuh intrik, bahkan bisa dipengaruhi kekuatan politik atau permainan hukum yang kotor. Jika terbukti secara administratif bahwa aset tertentu merupakan hasil dari kejahatan, maka aset tersebut bisa langsung disita dan dikembalikan kepada negara. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Fakta bahwa banyak koruptor tetap hidup nyaman meski telah dipenjara adalah tamparan keras bagi sistem hukum kita. Mereka masih memiliki kekayaan, aset properti, kendaraan mewah, bahkan perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi di bawah nama keluarga atau orang kepercayaan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan bahwa aset-aset tersebut berasal dari hasil kejahatan karena tersamar dalam alur transaksi yang kompleks. Namun, dengan adanya peraturan yang memperbolehkan perampasan aset berbasis pembuktian administratif, maka celah-celah ini dapat ditutup dengan lebih efektif.
Jika kita menganggap serius korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka pendekatan yang kita gunakan juga harus luar biasa. Tidak ada alasan untuk terus bersikap lunak terhadap pelaku kejahatan yang telah merampas hak-hak rakyat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, penerapan hukuman mati terhadap koruptor bukanlah hal yang berlebihan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya sudah membuka ruang untuk menjatuhkan pidana mati, terutama bila korupsi dilakukan dalam keadaan darurat atau menyangkut kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
Penerapan hukuman mati terhadap koruptor memang menuai kontroversi, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Tetapi perlu diingat, konstitusi kita, dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, memberikan batasan terhadap kebebasan individu bila bertentangan dengan kepentingan umum dan moral publik. Dalam kasus korupsi besar yang berdampak pada rusaknya pelayanan publik, kelaparan, pendidikan yang terhambat, hingga kematian akibat tidak tersalurkannya anggaran kesehatan, maka pelaku layak dianggap sebagai penjahat kemanusiaan. Negara harus hadir secara tegas untuk memastikan bahwa tidak ada ruang aman bagi kejahatan seperti ini.
Kita pun harus menyadari bahwa korupsi tidak lagi bisa dianggap sebagai kesalahan individu semata, tetapi telah menjadi bagian dari jaringan sistemik yang kuat. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara, melainkan merampas masa depan rakyat. Dana bantuan sosial yang dikorupsi adalah hak warga miskin yang lapar. Dana pendidikan yang digelapkan adalah hak anak-anak untuk belajar dan meraih mimpi. Dana kesehatan yang disunat adalah nyawa rakyat yang terancam. Dalam kondisi seperti ini, menempatkan koruptor pada posisi sebagai musuh negara bukanlah sikap emosional, melainkan bentuk keadilan yang hakiki.
Tak bisa kita pungkiri, selama ini vonis terhadap para koruptor cenderung ringan dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Bahkan beberapa pelaku yang terbukti korupsi dalam jumlah besar hanya divonis beberapa tahun penjara, lalu mendapatkan potongan remisi, dan akhirnya keluar lebih cepat. Ini memperkuat kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Publik muak menyaksikan realitas ini berulang-ulang, seolah sistem hukum tak mampu menyentuh orang-orang yang memiliki kuasa dan uang. Dengan adanya UU Perampasan Aset, harapan untuk memiskinkan para koruptor bukan lagi sekadar slogan. Negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyita seluruh kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, bahkan jika telah dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, atau fasilitas kesehatan masyarakat. Tidak ada alasan menunda lebih lama. Setiap hari yang kita lewatkan tanpa peraturan ini berarti memberi waktu lebih lama bagi para koruptor untuk menyembunyikan harta, menyamarkan aset, dan memperluas jaringan kejahatannya.
Kini bola ada di tangan DPR dan pemerintah. Rakyat menunggu keberanian politik yang nyata, bukan basa-basi dan janji-janji normatif yang tak kunjung dibuktikan. Jika DPR benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, maka tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU Perampasan Aset. Bila negara serius ingin menghapus budaya korupsi, maka langkah pertama adalah mencabut keuntungan ekonomi dari praktik tersebut. Setelah itu, barulah keadilan bisa ditegakkan secara utuh: koruptor dimiskinkan, diadili dengan tegas, dan jika perlu, dijatuhi hukuman mati atas pengkhianatannya terhadap bangsa.
Korupsi adalah musuh bersama. Sudah waktunya kita bertindak lebih tegas dan berani. Bukan sekadar memberi efek jera, tetapi juga memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi pilihan yang menguntungkan. Negara tidak boleh kalah. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dan jika tidak tegas, sampai kapan kita terus dikibuli oleh para penjarah uang rakyat?
Bionarasi Penulis:
Agung Wicaksono, S.H., M.H., lahir di Balikpapan pada 15 Agustus 1991. Merupakan alumni S-1 Hukum Universitas Mulawarman dan S-2 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris. Saat ini berprofesi sebagai advokat di kantor Biro Bantuan Hukum (BBH) Balikpapan dan aktif dalam kegiatan hukum serta advokasi sosial kemasyarakatan. Selain aktivitas profesional, penulis rutin menyampaikan gagasan hukum melalui tulisan opini di berbagai media massa sebagai bentuk kontribusi intelektual demi memperkuat kesadaran hukum masyarakat.